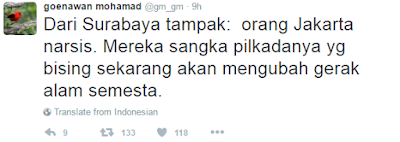|
| via Okezone News |
Catatan
penulis: cerita ini saya dengar dari seorang penjual angkringan di Yogyakarta. Saya
tidak bisa memastikan keakuratan cerita tersebut.
Penjual angkringan dari
Wonosari itu baru satu setengah tahun kerja di Jakarta. Berbekal ijazah SMP,
dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang pebisnis di daerah
Pondok Indah. “Saya tidak tahu bisnisnya apa, tetapi dia kaya. Orang Jepang,” tuturnya
soal sang majikan.
Jakarta, dan Indonesia
secara umum, saat itu memang keterlaluan. Krisis ekonomi membuat harga barang
melambung terlampau tinggi. Dia awalnya bekerja di sebuah bengkel, tapi bengkel
itu bangkrut. Hubungan pertemananlah yang membuatnya bisa bekerja di rumah
orang Jepang itu. Untungnya dia betah karena tak merasakan langsung dampak
krisis. Makanan tersedia di rumah, juga tidak ada margin keuntungan yang
dikejar karena gajinya dibayarkan bulanan.
Namun, seperti tak bisa
ditolak, tibalah masa-masa kelam itu. Entah berawal dari mana (atau dari
siapa!) kebencian terhadap orang Tionghoa menyebar luas di kalangan orang “pribumi.”
Kebencian itu sebegitu hebatnya hingga membakar nalar dan menghanguskan nurani.
Kondisi demikian, ditambah perut yang kian hari kian kosong, membuat salah satu
tragedi kemanusiaan di Jakarta tak bisa dicegah.
***
 |
| via backupblog77.blogspot.com |
Pada suatu malam, berita
tentang kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah di Jakarta sudah terdengar.
Sasarannya adalah orang Tionghoa. Rumah-rumah mereka diserbu. Mereka yang
terlihat di jalanan dibantai tanpa ampun. Dibakar hidup-hidup ataupun disabet
pedang. Toko-toko mereka dijarah. Para perempuan ditelanjangi dan diperkosa
secara bergilir dengan terang-terangan, sebelum akhirnya dibunuh juga dengan
keji.
Paginya, dengan perasaan
was-was, sang majikan nekat minta diantar oleh sopir untuk pergi ke kantor. “Sopir
itu orang Pacitan, mas. Dia awalnya sudah ragu-ragu, karena semalam masih rusuh
di mana-mana. Bapak [majikan] kan orang Jepang, wajahnya kayak Cina, bisa ikut
dibantai juga,” katanya.
Sembari tak henti menyebut
nama kebesaran Allah, majikan dan sopir meluncur mempertaruhkan nyawa di
jalanan Jakarta. Lantas tragedi itu tak bisa dihindari. Di tengah perjalanan
mobil mereka dihentikan oleh kerumunan yang membawa bensin. Melihat wajah
oriental, bensin langsung diguyurkan ke mobil lalu disulut. Sang majikan dan
sopir terjebak di dalam mobil. Mereka hangus terbakar.
Kabar soal itu cepat
sampai di rumah. Seketika aura rumah menjadi sangat berbeda. Sang istri, juga
orang Jepang, langsung membayar gaji para pekerja di rumahnya saat itu juga.
Dia minta dirinya dan anaknya dilindungi sambil berlinang air mata. Pada suatu
kesempatan yang baik, dia lalu bisa diantar sambil dijaga ke bandara untuk
kemudian terbang ke luar Indonesia.
***
 |
| via myrepro.wordpress.com |
Penjual angkringan lalu
tiba kembali di Wonosari yang adem ayem. Tak hanya bawa uang, dia juga bawa
memori mengenaskan dari Ibukota. Soal darah, pemerkosaan, air mata, isak
tangis, dan tubuh-tubuh bergelimpangan yang tak jelas akan diapakan.
Menurutnya, kejadian
paling mengerikan adalah pembakaran sebuah gedung pusat perbelanjaan berlantai
tiga. Sekelompok warga yang seperti kesurupan itu membakar lantai satu. Asap dan
apinya membaut ratusan orang di lantai satu hingga tiga mati lemas lalu
terpanggang. Bukan orang Tionghoa saja yang jadi korban. “Campur-campur,”
tegasnya.
“Itu pelakunya enggak bisa
diusut mas?” tanyaku. “Kayaknya enggak mas. Wong itu kerusuhan kok. Kacau
banget. Pelakunya banyak, rakyat Indonesia. Jawa, Flores, Batak, gabung jadi
satu,” jelasnya sambil menyalakan rokok.
Barangkali pandangannya
agak bias soal istilah rakyat, pribumi, Cina, dan semacamnya, tapi itulah
realitas yang ada di benak banyak orang. Baik atau buruk, benar atau salah,
etis atau tidak, realitanya memang itulah yang terkonstruksi di benaknya.
“Kalau pelakunya termasuk
orang Jawa dan itu atas nama rakyat, panjenengan ikut mbantai gak mas?” tanyaku.
Lugas. Bodoh juga, barangkali. Karena kalau iya, saya berhadapan dengan
pembunuh keji. Minum teh yang diaduk oleh tangan berlumuran darah nyaris dua
puluh tahun lalu.
“Enggak mas. Tapi saya
ikut diajak njarah,” jawabnya (saya jadi sedikit lega). Penjarahan toko-toko
tak terhindarkan dari kerusuhan itu. Warga yang anonim itu memasuki toko-toko
besar, mengeluarkan isinya, mengambil segala yang bisa diambil. Membawa pergi
apa-apa yang bernilai cukup tinggi dan
bisa dibawa pakai tangan.
“Kebanyakan pada ambil
alat elektronik yang bisa dibawa, mas. Kalau saya malah ambil susu. Hla itu
susunya dibuang di jalan-jalan, saya kumpulin aja. Itu kalau diminum tiap hari,
empat bulan baru habis mas,” ujarnya sambil menunjukkan seberapa tinggi
tumpukan susu yang dia kumpulkan. Kira-kira setinggi pinggangnya.
“Waktu itu panjenengan
umur berapa?”
“Tujuh tahun, mas.”
“Berarti belum mudeng ya
waktu itu rusuh?”
“Belum, mas. Tapi saya sering
dengar istilah ‘Cina singkek’ di sekolahan. Lagian kayaknya Jogja enggak rusuh
mas.”
“Menurut panjenengan,
bakal ada kerusuhan lagi nggak mas soal ras tadi? Kan ramai lagi tuh di
Jakarta,” saya balik bertanya.
“Hahaha.. iya. Sekarang
apa-apa mahal, tapi semoga enggak terjadi [kerusuhan] lagi. Sing penting aman, selamet. Urip kuwi ora golek
banda, tapi golek selamet,” katanya yang tiba-tiba terdengar bijak.
***
Sementara pembeli mulai
ramai berdatangan karena hujan mulai reda. Mahasiswa senang makan di angkringan
sambil nongkrong, sementara mahasiswi memilih untuk beli ‘nasi kucing’, lauk,
dan minuman yang diplastik.
“Hati-hati, mas. Besok
mampir lagi,” ucap penjual angkringan seiring kakiku memutar pedal. (*)